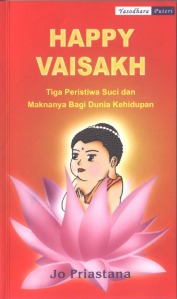Beribukota Naypyidaw yang diresmikan pada 6 November 2005 oleh pemerintahan junta militer sebagai pengganti ibukota sebelumnya Yangon, negara Myanmar yang dahulu bernama Burma memiliki komposisi penduduk terbesar 89% beragama Buddha dan etnis Burma sebesar 68%. Mayoritas penduduk ini hidup berdampingan dengan etnis lainnya Shan (9%), Kayin (7%), Rakhine (4%), Mon (2%), Kayah dan Kachin, dan penganut agama Kristen (4%), Islam (4%), dan lainnya (3%). (Kompas, 11/10/07).
Karena itu, negara dengan jumlah penduduk 48.798.000 jiwa (Juli 2007) yang memiliki pagoda Swedagon yang menjulang di kota Yangon sebagai identitas nasional Burma dapat dikatakan sebagai negara Buddhis terbesar di Asia Tenggara, berdampingan dengan negeri tetangganya yang juga berpenduduk mayoritas Buddhis seperti Laos, Thailand, China. Kini para bhiksu yang berakar dalam masyarakatnya itu tengah berhadapan dengan penguasa negerinya sendiri yang mengerahkan para serdadunya mengobrak-abrik vihara.
Diperkirakan negara yang dikenal juga sebagai negara seribu pagoda ini memiliki puluhan ribu bhiksu/bhikkhu yang mendiami puluhan ribu vihara-vihara pada negara seluas 676.578 km2 yang memikiki perbatasan darat dengan Thailand, China, India, Laos dan berhadapan dengan Samudera Hindia. Para bhiksu/bhikkhu di Myanmar yang belum lama ini pada September 2007 lalu melakukan aksi perlawanan secara damai terhadap junta militer merupakan strata social yang sejak dahulu kala memiliki pengaruh luas dan telah berakar jauh dalam masyarakat Myanmar.
Sejarah kehidupan kebhiksuan di Myanmar ini juga tak lepas dari negeri Srilanka yang menjadi sumber dari mana pergerakan agama Buddha menyebar ke Asia Tenggara, khususnya agama Buddha bermashab Theravada. Dalam buku Edward Gonze, “A Short History Buddhism,” Allen and Unwin, London-Boston, 1980, terungkap bahwa agama Buddha telah masuk ke Burma sejak abad ke 5 dan abad ke 6, baik agama Buddha Theravada maupun agama Buddha Mahayana.
Namun jauh sebelumnya, dikabarkan pula bahwa negeri yang terkenal dengan sebutan Suvannabhumi ini jauh sebelumnya di sekitar abad ke 3 SM telah memiliki kontak dengan sekelompok pedagang dari Jambudipa, sebutan untuk negeri India. Menurut sumber sejarah seperti yang terdapat dalam Mahavamsa, disebutkan bahwa pada abad ke SM itu terdapat dua orang bhikkhu dari India yang bernama Sona dan Uttara menyebarkan Dhamma ke negeri Suvannabhumi.
Sedangkan adanya suatu organisasi yang kuat bagi pejalan kebhikkhuan di Myanmar itu sendiri baru terbentuk pada abad 9, yaitu yang menamakan dirinya “Ari” (dari kata arya yang berarti mulia). Dikabarkan agama Buddha yang ada itu adalah agama Buddha Pala yang berasal dari Bihar, India dan Bengal yang bermashab Mahayana dan juga menyerap kepercayaan setempat. Baru awal periode tahun 1000 agama Buddha di Burma ini berubah karakternya dengan mengambil inspirasi pada Buddha yang berasal dari Srilanka, yang diprakarsai oleh Raja Anawrahta dari Pagan di tahun 1057 yang mendatangkan bhiksu-bhiksu dan kitab suci dari Ceylon, Srilanka.
Sejak itulah kelompok bhiksu Mahayana dan juga Vajrayana memudar pengaruh dan dominasinya, meski keberadaannya tidak lenyap bahkan hidup terus sampai akhir abad 18. Kehidupan kebhikkhuan beralih kepada mashab Theravada yang mendapat perlindungan istana, sehingga tumbuhlah kebudayaan Buddhis dengan peninggalannya yang sangat bagus dan indah.
Semasa kekuasaan Narapatisithu (1173-1210) banyak vihara dibangun dibawah para sponsor seperti Sulamani, Gawdawpalin juga untuk penulisan kitab suci Pali. Chapata yang juga dikenal sebagai Saddhammajotipala menulis suatu seri karya mengenai tata bahasa Pali, disiplin vinaya dan filsafat seperti: Suttanidesa, sankhepavannana, Abhidhammatthasangha. Sementara pujangga lainnya yang bernama Sariputra menulis karya yang merupakan koleksi pertama mengenai komposisi hukum kesunyataan yang dikenal sebagai Dhammavilasa atau Dhammathat.
Kebudayaan Buddhis yang tumbuh semarak pada masa itu dikabarkan tercermin dengan tumbuhnya 9000 ribu pagoda dan vihara yang memenuhi tanah seluas delapan mil, diantaranya yang paling terkenal adalah Vihara Ananda dari abad ke 11. Dalam Vihara ini terdapat 547 cerita Jataka yang dikisahkan di atas tanda peringatan atau piagam yang dibuat dari lapisan kaca. Hal ini berlangsung selama tiga abad sebelum kekuasaan Pagan itu dihancurkan oleh Bangsa Mongol pada tahun 1287.
Meski, setelah runtuhnya dinasti Pagan ini, dan selama 500 tahun ke depan Burma terbagi-bagi dalam kerajaan-kerajaan yang saling berperang, namun tradisi Theravada tetap berlanjut walau tidak semerbak periode sebelumnya, bahkan raja Dhammaceti dari Pegu di akhir abad 15 memperkenalkan kembali pergantian pimpinan vihara yang sesuai kitab suci dari Ceylon.
Pada tahun 1752, Burma mengalami penyatuan kembali, dan setelah tahun 1852 Sangha memperoleh perlindungan, dan sebuah dewan di Mandalay memperbaiki teks Tipitaka pada tahun 1868-71 yang kemudian diukir di atas 729 lempengan pualam. Namun, kedatangan kolonial Inggrias di tahun 1885 sangat merugikan perkembangan agama Buddha dan Sangha karena mereka banyak menghancurkan tempat-tempat suci, dan sejak itu pula para bhiksu memainkan peranan penting dalam perjuangan merebut kemerdekaan.
Sangha yang merupakan komunitas bhiksu tidaklah asing bagi rakyat Burma. Rakyat disamping masih memiliki kepercayaan leluhurnya yakni para Nat atau “roh” yang diminta menolong mereka juga memiliki kepercayaan tentang cara utama untuk memperoleh kebajikan yaitu dengan membangun pagoda atau vihara. Bisa dimengerti bila Burma memiliki banyak pagoda, dan vihara-vihara selalu berada di pusat-pusat tempat tinggal mereka, dimana vihara-vihara itu juga berfungsi sebagai tempat pendidikan tempat rakyat melek huruf.
Bersama Sangha yang mendapat tenpat di hati rakyat, agama Buddha menjadi kekuatan yang memberikan karakteristik peradaban Burma. Sesungguhnya, agama Buddha yang dibabarkan oleh Sang Buddha ini sepanjang sejarahnya telah memicu kehidupan social yang demokratis dan non-materialistis bagi bangsa Burma, disamping membawa keindahan pengetahuan, etika kehidupan yang menekankan kesederhanaan yang semuanya itu merupakan sumber nilai untuk terciptanya perdamaian dan kebahagiaan.
Namun, melihat perkembangannya yang ada kini, dan juga jaman yang bergerak cepat, rupanya persoalan Burma atau Myanmar kini, hubungan antara agama dan negara, antara komunitas Sangha dan para pemimpin pemerintahan tidaklah sesederhana sebagaimana nilai-nilai nan indah itu dikumandangkan. Sewaktu U Nu berkuasa, U Nu berupaya menghidupkan kembali Buddhisme seperti semasa kerajaan yang jaya dulu, namun U Nu tidak dapat bertahan lama dan Burma pun terbelenggu masuk dalam genggaman dictator militer yang kaku dan membosankan.
Kini ditengah tantangan kehidupan bangsanya yang berada dibawah kendali junta militer, para bhiksu yang telah membudaya itu tetap berupaya melakukan reposisinya dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga kehidupan masyarakatnya. Para bhiksu dipaksa jaman dan terpaksa harus menghadapi tantangan social politis yang terbentang keras itu dengan bangkit dan bergerak ke jalan dalam dami demi mewujudkan nilai-nilai buddhadharma tetap berakar dan demi tetap berada di hati rakyat yang sepanjang sejarah menjadi pendukung sejati jalan kesuciannya. (jo priastana).